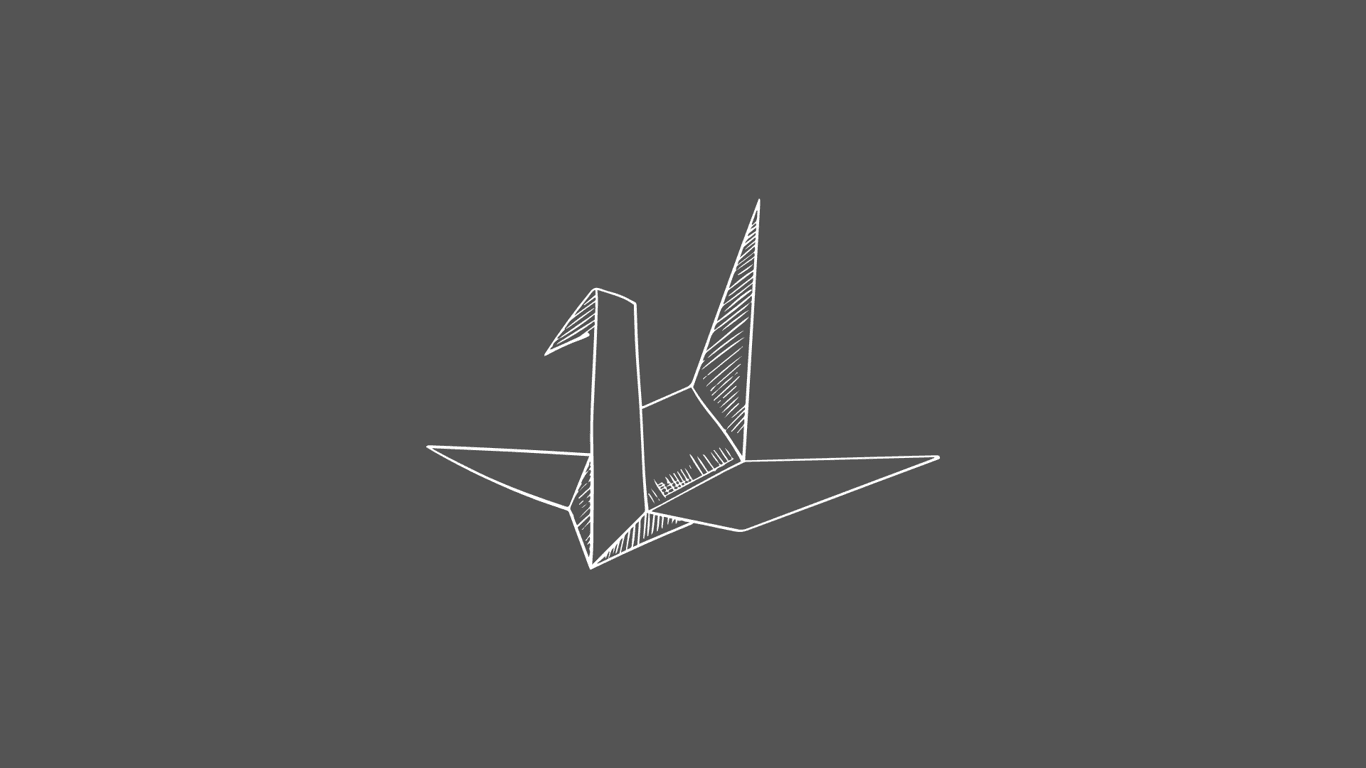Oleh: Anur Al Hadyd

Pagi itu, udara dingin menyentuh kulit. Saya mengenakan pakaian sederhana, namun hati dipenuhi dengan antusiasme. Hari itu bukan sekadar tentang sebuah acara, bukan hanya tentang buku, melainkan tentang perjalanan bersamanya, Sabrina Khaerani —seseorang yang setiap kehadirannya menjelma seperti puisi tanpa jeda.
Dengan sepeda motor, kami bergegas menuju acara bertajuk Membaca Raden Saleh. Di tengah perjalanan, langit yang semula mendung mulai meneteskan hujan, mengiris tipis-tipis udara yang sebelumnya tenang. Kami menepi, berteduh sejenak di bawah naungan, lalu mengenakan jas hujan. Tangannya sibuk memasang jas hujannya, juga memastikan jas hujan saya terpasang dengan baik. Di tengah dinginnya hujan, ada kehangatan yang tak terucapkan—mungkin karena caranya menjaga hal-hal kecil.
Sesampainya di Universitas Indonesia, kami mencari tempat parkir dan melangkah menuju gedung IV Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Di dalam acara, saya duduk di sampingnya. Sambil beberapa orang maju ke depan untuk membacakan, kami membuka buku dan mulai membaca bersama. Bab Cianjur, sebuah novel "Pangeran dari Timur" karya Iksaka Banu dan Kurnia Effendi, kami telusuri bersama dengan penuh rasa.
Setelah acara usai, kami menuju Musholla untuk menunaikan salat Zuhur, lalu melanjutkan langkah mencari tempat makan di sekitar. Dari kejauhan, tampak sebuah bangunan berwarna putih —benar, itu sebuah kantin. Kami menyusuri deretan penjual makanan, mengelilingi berbagai pilihan. Hingga akhirnya, kami berhenti di depan penjual mie, yang kebetulan berada tepat di hadapan kami. Kami memilih meja di dekat sana, duduk berdua saling berhadapan. Semangkuk mie tersaji di tengah-tengah, ditemani obrolan ringan yang berarti, seperti bumbu tambahan yang melengkapi kehangatan.
Langit yang semula mendung perlahan cerah, seolah mengundang kami untuk berkeliling di sekitar. Langkah demi langkah kami menyusuri jalan menuju tepian danau, membiarkan ketenangan menyusup ke dalam diri. Di sana, momen terabadikan dalam senyuman yang tulus—jejak kecil yang akan selalu di kenang.
Nampaknya siang merangkak perlahan menuju sore, dan akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Sebelum beranjak, saya memberikan sebuah buku kepadanya, "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini". Buku yang berisi tulisan-tulisan yang ingin saya bagikan dengannya, berharap ia menemukan sesuatu yang berarti di dalamnya.
Dalam perjalanan, suara kaca helmnya yang terus turun berkali-kali menghadirkan tawa kecil bersama—tawa yang memecah keheningan, sekaligus mengisi jeda di antara obrolan ringan sepanjang jalan.
Di tengah perjalanan pulang, dia bertanya, "Capek nggak?" Saya menggeleng, "Enggak." Lalu dia melanjutkan, "Mau es krim?" Saya menjawab, "Mau, dimana?" , "Mau yang dekat atau yang jauh? " tanyanya lagi, memberi saya pilihan. "Aku ikut kamu" , jawab saya, suara kami terdengar di antara deru angin. "Kita ke tempat es krim favorit aku", katanya. Saya mengiyakan, kami pun bergegas ke toko es krim itu. Roda motor terus berputar perlahan, membelah jalan yang mulai lengang, sementara angin sore terus bertiup.
Dalam perjalanan menuju toko es krim, kami mampir ke sebuah Masjid terlebih dahulu untuk salat Ashar. Saya bersyukur untuk hari itu, untuk momen-momen kecil yang Tuhan titipkan, dan untuk dia yang menjadi bagian dari setiap doa-doa dan harapan.
Selepas kami salat Ashar dan hendak beranjak ke tempat tujuan, cuaca tiba-tiba berubah. Awan mendung menggantung di langit, dan gerimis kembali turun. Kami saling berpandangan, lalu memutuskan untuk pulang. Es krim yang semula menjadi tujuan batal kami kunjungi. Di sepanjang perjalanan pulang, lagi-lagi suara kaca helmnya mengisi jeda di antara obrolan kami sepanjang jalan, menciptakan tawa kecil dan menghapus sisa-sisa dingin yang dibawa oleh gerimis.
Kami semakin dekat dengan tujuan pulang, namun gerimis semakin turun. Ia meraih jaket yang dipegangnya, lalu dengan lembut menaruhnya di pundak saya. Saya tetap melaju dengan motor, membiarkan kehangatan kecil itu menjadi pelindung di tengah udara yang mulai dingin. Tak lama kemudian, kami akhirnya sampai, sementara sisa gerimis, meski tak deras, masih menari halus di udara, seperti irama penutup dari perjalanan kami hari itu.
Sembari itu, saya sadar akan sesuatu: hari itu bukan hanya soal acara, bukan hanya soal hujan yang turun, bukan pula soal es krim yang batal. Semua tentang momen-momen kecil yang Tuhan susun dengan lembut, membuat hari itu menjadi lebih sempurna. Saya tahu, es krim favoritnya akan tetap menunggu di lain waktu. Seolah Tuhan berkata, "Hari ini cukup untuk membuatmu bersyukur. Untuk esok, aku siapkan keindahan yang lain." Dan saya percaya, setiap perjalanan, sekecil apa pun, selalu memiliki cerita untuk dikenang—sesederhana itu, namun begitu bermakna.
14 Desember 2024. Universitas Indonesia